Kino - Haruki Murakami #part1 [terjemahan]
PS: Cerpen ini saya terjemahkan dari versi bahasa Inggrisnya yang diterbitkan di web The New Yorker oleh Philip Gabriel yang sebelumnya telah menerjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Jepang.
Pria itu selalu
duduk di tempat yang sama, jauh dari sudut bar. Dan dia bisa ditemukan saat
tempat itu sepi, tapi bagaimanapun, tempat itu memang hampir selalu sepi.
Jarang terlihat ramai. Kursi-kursi yang disediakan pun tak menarik minat dan
tak begitu nyaman. Tangga di belakang ruangan bahkan membuat langit-langitnya miring
dan rendah, sehingga susah untuk berdiri tanpa menubrukkan kepala. Tubuh pria
itu tinggi, tapi, beberapa hal membuatnya lebih menyukai tempat yang sempit.
Kino ingat
betul, saat pertama kali pria itu masuk kedai, penampilannya langsung menarik
perhatian—wajah biru bekas cukuran, tubuh kurus tapi berbahu lebar, mata tajam
berkilat, rahang tegas dengan dahi lebar. Usianya sekitar awal tiga puluhan,
memakai jas hujan panjang berwarna abu-abu—meskipun tidak sedang hujan. Saat pertama
melihatnya, Kino mengira pria itu anggota yakuza dengan pengawal di kiri kanan.
Saat itu jam tujuh lebih tiga puluh menit pada malam pertengahan April yang
dingin. Bar sedang sepi. Pria itu memilih duduk di pojok, menaruh jaketnya dan
memesan bir dengan suara rendah. Ia lantas tenggelam dalam buku tebal. Setengah
jam setelahnya, begitu birnya habis, ia mengangkat tangan sekitar satu atau dua
inci untuk memesan whiskey. “merek apa?” tanya Kino. Dan pria itu tak punya
pilihan.
“Scotch biasa. Ah,
Dobel. Tambahkan air dengan takaran yang sama, ditambah sedikit es.”
Kino menuang beberapa White Label ke dalam
gelas, menambah air dalam takaran sama dan dua balok es ukuran kecil, lalu
memberikannya kepada pria itu, yang sejurus kemudian langsung menyesapnya
sambil memerhatikan gelas dan menyipitkan mata. “Hmmm.. lumayan.”
Ia membaca lagi setengah jam berikutnya, lalu
berdiri dan membayar tunai. Tagihannya dihitung tepat agar tidak perlu dapat koin
kembalian. Begitu pria itu keluar, Kino mengembuskan napas lega. Tapi setelah
pergi, sosoknya malah menggantung di kepala. Selagi Kino berdiri di belakang
bar, ia melirik sesekali pada meja yang ditempati pria itu dengan sedikit
berharap, ia—pria itu—tetap duduk di sana, mengangkat tangan beberapa inci dan
memesan sesuatu.
Di kunjungan yang berikutnya, pria itu mulai
rutin datang ke bar milik Kino. Dia datang sekali—seringnya dua kali—dalam
seminggu, dan selalu memesan bir lebih dulu, kemudian baru whiskey. Terkadang
dia mempelajari menu harian lebih dulu di papan dan memesan makanan ringan.
Pria itu jarang bicara. Dia selalu datang saat
menjelang malam dengan buku terkepit di lengan. Dia menempati sudut bar seperti
biasanya. Begitu capek membaca, matanya teralihkan penuh pada botol-botol
minuman keras di depannya, memandangnya intens seolah sedang memeriksa bangkai
binatang dari kejauhan.
Sesekali Kino dimintai bantuan oleh si pria,
meskipun berada di dekat pria itu membuatnya tak nyaman—Sekalipun mereka hanya
berdua. Kino tak pernah membicarakan tentang dirinya, dan tak pernah kesulitan
untuk membiarkan suasana makin sunyi. Saat pria itu membaca, Kino mengerjakan
apa saja yang bisa dikerjakan, seperti menyuci piring, menyiapkan saus, memilih
lagu untuk diputar atau membuka-buka halaman koran.
Kino tidak tahu nama pria itu. Dia hanya
pengunjung biasa yang datang untuk menikmati sebotol bir dan wiski, membaca
dengan kusyuk, membayar tagihan, lalu pergi. Tak pernah membuat keributan
sedikit pun. Lantas, apa lagi yang perlu Kino ketahui tentang pria itu?
Kembali pada masa-masa kuliah, Kino saat itu sudah jadi pelari
hebat. Tapi baru saja di tahun pertama dia sudah mematahkan urat tumitnya.
Lantas dia menyerah untuk mengikuti tim olahraga lari. Setelah lulus,
berdasarkan rekomendasi pelatihnya, dia bekerja di sebuah perusahaan penyedia
perlengkapan olahraga, dan tinggal di sana selama tujuh belas tahun. Ia
bertanggung jawab atas penawaran barang agar toko-toko olahraga tetap memasok
produk-produk darinya. Tempatnya bekerja adalah persuahaan
level menengah yang bermarkas di Oklahama, dan jauh dari kata terkenal, juga
kalah secara finanasial dari Nike atau Adidas untuk mendapat kontrak kerja sama
ekslusif dengan pelari-pelari terbaik dunia. Tapi tetap saja, produknya dibuat
secara teliti dan bisa dikatakan berkualitas untuk atlit papan atas.
“Bekerjalah secara jujur dan itu akan terbayar” adalah selogan dari pemilik
perusahaan, dan selogan tersebut, bagaimanapun adalah pendekatan kuno yang
sesuai kepribadiannya. Meskipun pendiam, orang sepertinya bisa bekerja dengan
baik dalam penjualan. Lebih tepatnya, karena kepribadiannya yang disukai
sekaligus dipercaya pelatih, para atlit pun turut mempercayainya. Kino
betul-betul mendengarkan apa yang menjadi keinginan para atlit, lantas berusaha
sebisa mungkin meyakinkan kepala produksi untuk memenuhinya. Penghasilannya tak
seberapa, tapi ia puas dengan pekerjaannya. Meskipun tidak mampu berlari lagi,
ia suka melihat atlit-atlit tersebut berlari mengelilingi lintasan.
Kino lalu keluar dari pekerjaannya, bukan karena tidak puas dengan
apa yang ia kerjakan, melainkan karena istrinya memiliki hubungan gelap dengan
teman di tempatnya bekerja. Kino lebih banyak menghabiskan waktu di jalan
dibanding di rumahnya di Tokyo. Saat itu, Kino disibukkan dengan pekerjaannya:
mendatangi toko-toko penyedia alat olahraga di seluruh Jepang, dan mengunjungi
beberapa kolega dan juga sponsor lain untuk menawarkan sampel sepatu. Pada saat
itulah, istrinya mulai berselingkuh. Kino bukan tipe orang yang dengan mudahnya
memahami keadaan. Pikirnya, semua berjalan baik-baik saja dan tak ada yang
salah dalam pernikahannya. Kalau saja ia tak pulang lebuh dulu dari perjalanan
bisnisnya, ia mungkin tak akan memergoki apa yang terjadi pada istrinya.
Sekembalinya ke Tokyo, ia langsung ke apartemennya di Kansai dan
berjalan begitu saja tanpa curiga, hingga, kemudian mendapati istri dan teman
kantornya berpelukan di ranjang, tanpa busana. Istrinya berada di atas, dan
ketika Kino membuka pintu, pandangannya langsung tertuju pada wajah sang istri
dan payudaranya yang memantul ke atas-bawah. Usianya tiga puluh sembilan saat
itu dan mereka tak memiliki anak. Kino menundukkan kepala, menutup pintu
kamar, meninggalkan apartemen, dan tak
pernah kembali lagi. Hari berikutnya, ia keluar dari pekerjaannya.
Kino memiliki bibi yang belum menikah, yang merupakan kaka dari
ibunya. Sejak kecil, bibinya memang sudah baik padanya. Ia memiliki pacar yang
lebih tua darinya selama bertahun tahun, yang dengan murah hati memberinya
rumah kecil di Aoyama. Ia tinggal di lantai dua, dan menjalankan bisnis kedai kopi di lantai dasar. Depan rumahya,
dipasangi taman kecil dan pohon willow yang mengesankan, dengan daun rindang
yang menggantung rendah. Rumahnya yang berada di jalanan sempit di belakang
Museum Nezu, bukanlah tempat yang bagus untuk menarik perhatian pengunjung.
Tapi bibinya punya sesuatu yang membuatnya bisa menarik orang, dan akhirnya
kedai kopi tersebut berjalan dengan cukup baik.
Setelah berusia enam puluh tahun, ia memiliki sakit di punggung
yang membuatnya sulit menjalankan kedai seorang diri. Dia lalu memilih untuk
pindah ke resor di Izu Kogen Highland. “Aku penasaran apa kamu mau mengambil
alih toko ini?” tanyanya pada Kino. Itu terjadi sekitar tiga bulan sebelum Kino
mengetahui perselingkuhan istrinya. “saya menghargai tawaran itu,” ucapnya,
“tapi untuk sekarang ini, aku cukup senang berada di sini.”
Seusai mengajukan pengunduran dirinya di kantor, ia menelepon
bibinya dan bertanya apa ia sudah menjual toko tersebut. Rupanya, tempat itu
sudah didaftarkan di agen perumahan tapi belum juga ada tawaran serius yang
datang. “aku ingin membuka bar kalau boleh.” Kata Kino. “bisakah aku menyewanya
perbulan?”
“Gimana dengan pekerjaanmu?”
“Aku sudah berhenti beberapa hari lalu.”
“Bukannya istrimu tidak suka kamu berhenti bekerja?”
“Kita mungkin akan segera bercerai.”
Kino tidak memberitahu alasannya, dan bibinya pun tidak bertanya.
Ada hening beberapa saat di ujung telepon. Bibinya lalu memberitahu harga sewa
perbulan, jauh lebih rendah dari yang kino bayangkan. “Kurasa aku bisa
mengambilnya.”
Dia dan bibinya tidak pernah bicara sebanyak itu (ibunya melarang
Kino untuk dekat-dekat dengannya), tapi mereka terlihat seperti memiliki
pengertian satu sama lain. Ia tahu bahwa Kino bukan tipe orang yang akan
melanggar janjinya.
Kino menggunakan setengah dari tabungannya untuk mengubah kedai
kopi menjadi bar. Dia membeli beberapa perabotan sederhana, dan mendapatkan
meja bar panjang yang kokoh. Dia mengaplikasikan walpaper berwarna pastel,
membawa koleksi-koleksi kasetnya dari rumah, dan menatanya di lemari buku di
bar bersama LPs. Dia memiliki stereo yang lumayan—sebuah pemutar piringan hitam
Thorens, sebuah amp luxman, dan speaker dua arah JBL kecil—yang ia beli sejak
masih sendiri, sesuatu yang dianggap mewah pada saat itu. Tapi ia selalu suka
mendengarkan lagu-lagu jazz kuno. Itu hobi satu-satunya yang ia punya. Hobi
yang tidak pernah diceritakannya pada siapa pun. Saat kuliah dulu, Kino bekerja
paruh waktu sebagai bartender di sebuah pub di Roponggi, jadi ia tahu betul
bagaimana caranya meramu coktails.
Ia menamai pubnya Kino, lantaran tidak terpintas satu nama pun yang
lebih bagus dari itu. Di minggu pertama, dia tidak mendapati satu orang pun
pengunjung. Tapi dia tak sedikit pun gelisah. Bagaimana pun dia memang tidak mengiklankan
tempatnya. Bahkan tidak menaruh papan iklan yang dapat menarik pengunjung. Hari
itu dia menunggu saja dengan sabar, berharap ada yang penasaran dan mereka akan
menginjakan kakinya ke pub kecil di belakang jalan ini. Dia masih memiliki uang
pesangon dan istrinya belum meminta dukungan finansial apa pun. Dia sudah
tinggal serumah dengan sahabat lamanya itu dan mereka sepakat untuk menjual
kondominiumnya yang berada di Kansai. Kino tinggal di lantai dua di rumah
bibinya, dan seolah-olah, untuk sementara waktu, hal itu dianggapnya pantas-pantas
saja.
Selagi menunggu pelanggan pertamanya, Kino suka mendengarkan musik
apa saja dan membaca-baca buku yang
sudah lama ingin dibacanya. Seperti tanah kering yang menyambut hujan, dia
membiarkan saja keheningan, kesepian, dan kesendirian itu merasuk. Dia
mendengarkan potongan-potongan permainan piano solo Art-Tatum. Bagaimanapun,
lagu itu sangat cocok dengan suasana hatinya saat ini.
Dia kurang begitu yakin, tapi sudah tak ada lagi kemarahan
terhadap istrinya, atau pun orang yang tidur dengannya. Pengkhianatan itu
lumayan mengejutkan, tentu saja, tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai
merasa tak ada gunanya jika terus bersedih, seolah-olah ini adalah nasib yang
harus diterimanya. Selama hidupnya, dia belum pernah mencapai apa pun, dan
menjadi tidak produktif. Dia tidak membuat siapa pun bahagia, dan, tentu saja,
tak dapat membuat dirinya sendiri bahagia. Bahagia? Dia bahkan tidak yakin apa
itu bahagia. Perasaannya sangat tidak pasti, juga emosinya; seperti luka dan
amarah, kekecewaan atau pasrah, dan bagaimana pun semua itu harus dirasakan.
Yang dapat dilakukannya saat ini hanyalah menciptakan sebuah tempat di mana
hatinya—yang tanpa kedalaman dan esensi—bisa bertambat dan mencegahnya dari berkeliaran
tanpa arah. Bar kecil ini—yang dinamainya Kino, yang bertempat di sudut
belakang jalan—adalah tempat tersebut. Dan, tempat itu juga—yang bukan karena
desainnya, tentu saja—secara aneh menjadi ruang yang kemudian memberinya rasa nyaman.
Bukanlah seseorang yang pertama kali menemukan tempat tersebut,
melainkan seekor kucing betina berbulu lebat dan panjang yang warnanya abu-abu.
Si kucing memilih tempat tak mencolok di pojok bar itu untuk meringkukkan
tubuhnya. Kino tak banyak menaruh perhatian padanya, dan begitu pun si kucing.
Sekali sehari, dia memberinya makan dan mengganti minumnya, tidak lebih dari
itu. Dan dia lalu membuat pintu kecil untuk kucing itu supaya bisa keluar masuk
bar kapanpun dia mau.
Kucing itu mungkin telah membawa keberuntungan bagi Kino. Sesudah
kedatangannya, bar tersebut mulai kebanjiran pelanggan. Beberapa dari mereka
bahkan datang secara berkala—mereka menyukai bar kecil dengan pohon tua yang
mengagumkan ini, juga pemiliknya yang berusia tiga puluhan, potongan hitam tua
yang berputar pada pemutar musik, dan kucing abu-abu yang selalu meringkuk di
sudut bar.
Seorang pria muda dengan kepala seperti habis dicukur datang ke
bar sekitar dua bulan setelah bar itu dibuka. Dan itu adalah dua bulan yang lain
sebelum Kino tahu namanya, Kamita.
Saat itu sedang hujan kecil, hujan dimana kamu akan ragu apakah
perlu menggunakan payung atau tidak. Dan waktu sedang menunjukkan jam setengah
delapan. Hanya ada tiga pengunjung di sana, Kamita dan dua pria berjas. Seperti
biasa, kamita duduk paling jauh dari konter, menyesap white labelnya dengan air
putih dan mulai membaca. Dua pria duduk di kursi, meminum satu botol Pinot
Noir. Mereka membawa sendiri botol minumannya dan bertanya apa boleh minum di
sini dengan membayar lima ribu yen. Itu pertama kalinya bagi Kino, tapi tak ada
alasan baginya untuk menolak. Dia membuka botol itu dan menuangkannya pada dua
gelas wine, beserta mengambil semangkuk berisi kacang-kacangan. Tidak ada yang
salah dari keduanya, meskipun mereka terlalu banyak merokok, yang bagi Kino
adalah hal yang sangat menjengkelkan. Tanpa ada yang perlu dikerjakan lagi,
Kino pun duduk di kursi dan mendengarkan LP Coleman Hawkings dengan trek
“Joshua Fit the Battle of Jericho.” Dia mendapati permainan bas solo pada Major
Halley sungguh luar biasa.
Pada awalnya, dua pria hanya terlihat mengobrol biasa, menikmati
wine-nya, tapi kemudian, perbedaan pendapat muncul pada beberapa topik dan lain
hal—yang mana kino tak tahu—dan mereka menjadi kian emosi. Sesaat setelahnya,
salah satu di antara mereka berdiri dan menggebrak meja dan menumpahkan isi
dalam asbak, salah satu gelas wine pecah ke lantai. Kino cepat-cepat mendekat
dan bergegas membersihkan, mengembalikan gelas dan asbak ke atas meja.
Kamita—meskipun saat ini, Kino baru saja tahu namanya—benar-benar jijik
dengan kelakuan kedua pria itu.
Expresinya pun tidak berubah, meskipun dia tetap mengetuk-ngetukkan jarinya
secara pelan pada meja konter seperti pianis yang tengah memeriksa kunci nada.
Aku harus segera mengontrol situasi buruk ini, pikir Kino. Dia mendekati pria
itu. “maaf,” ucapnmya sopan, “apa anda keberatan untuk memelankan suara anda
sedikit saja.”
Salah satu di antara mereka melemparkan tatapan dingin ke arah
Kino dan mulai beranjak dari kursi. Kino tidak memperhatikan sebelumnya kalau pria
itu benar-benar besar. Dia tidak begitu tinggi, tapi seperti halnya petarung
sumo, dia memiliki dada yang lebar dan berlengan besar.
Pria yang satunya bertubuh lebih kecil. Kurus dan pucat, dengan
tampang licik, tipe yang mahir dalam menghasut orang lain. Pria itu pelan-pelan
juga beranjak dari kursinya, dan kino mendapati dirinya bertatap muka dengan
kedua pria tersebut. Mereka berdua rupanya memanfaatkan kesempatan ini untuk
menghentikan perselisihan di antara mereka dan bersama-sama berkonfrontasi
melawan Kino. Tindakan mereka terlihat rapih dan terkordinir, seolah-olah sudah
sejak tadi menuggu kesempatan ini datang.
“Jadi, kamu pikir kamu bisa mengganggu kami?” pria bertubuh besar
mulai berbicara, suaranya terdengar kembang kempis.
Baju yang mereka kenakan terlihat mahal, tapi dari dekat akan
terlihat norak dan terkesan dibuat sembarangan. Mereka terlihat bukan seperti
anggota yakuza, tapi apa pun itu, yang mereka kerjakan bukanlah hal yang
terhormat. Pria yang lebih besar
memiliki potongan rambut yang sangat pendek, sementara temannya berambut coklat
dan ditarik ke belakang seperti ekor kuda.
“Permisi,” suara lain muncul.
Kino berbalik dan menemukan Kamita berdiri di belakangnya.
“Jangan salahkan karyawan,” kata Kamita, menunjuk Kino. “Saya yang
memintanya untuk melerai kalian. Anda membuat saya tidak bisa konsentrasi untuk
membaca.”
Suara Kamita terdengar lebih rendah dan lesu dari biasanya. Tapi
sesuatu yang tak kasat mulai muncul.
“Tidak bisa konsentrasi,” pria yang lebih kecil mengulangi ucapan
Kamita, seolah-olah meyakinkan tidak ada yang salah dalam kalimat tersebut.
“Bukankah kamu punya rumah?” giliran pria yang lebih besar kini bertanya.
“Tentu,” balas Kamita. “Saya tinggal dekat sini.”
“Lalu kenapa nggak pulang dan baca saja di rumah?”
“Saya lebih suka membaca di sini,” jawab Kamita.
Kedua pria tersebut bertukar pandangan.
“Berikan bukumu,” ucap pria yang lebih kecil. “Saya akan
membacakannya untukmu.”
“Saya suka membacanya sendiri, di tempat sepi,” jawab kamita, “
dan saya benci kalau kalian salah mengucapkan kalimat dalam buku ini.”
-- See you on the next part --
Segini
saja dulu, sisanya masih diedit-edit. Saya upload aja sedikit-sedikit
biar postingannya nggak panjang-panjang amat. Soalnya cerpen aslinya
panjang banget. 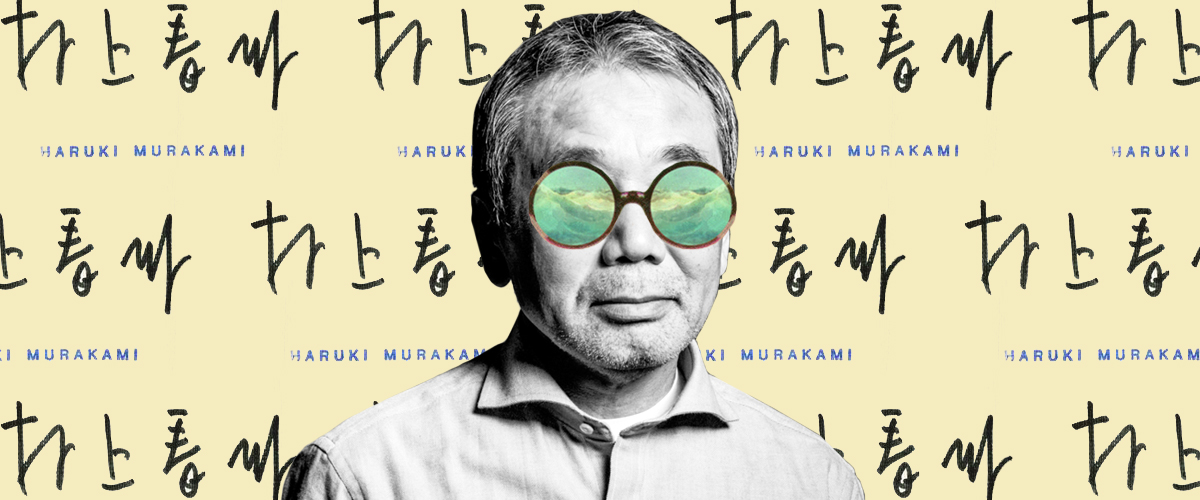

Waw. Masih akan di lanjutkan kah?
BalasHapusIya, ditunggu ya :)
Hapus